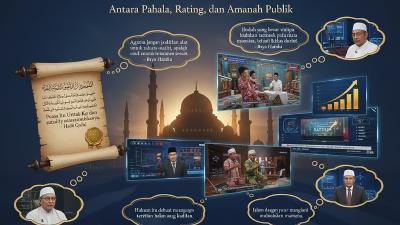Ketika Suara Moral Kehilangan Gaungnya

RAJAMEDIA.CO - DI TENGAH riuh politik dan kegaduhan sosial, Presiden Prabowo Subianto pada akhir Agustus 2025 mengundang 16 organisasi masyarakat keagamaan ke Hambalang, Bogor. Pertemuan itu membahas tantangan kebangsaan dan mencari cara menjaga suasana tetap damai serta kondusif. Hadir di antaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Mathlaul Anwar (MA), Dewan Dawah Islamiyah Indonesia (DDII), hingga Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII).
Dalam kesempatan lain, KH. Embay Mulya Syarief menegaskan pentingnya ketenangan dan rasa aman sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Kalau tidak ada ketenangan, maka kebutuhan yang lain pun tidak ada gunanya, ujarnya. Ia juga mendukung langkah tegas kepolisian menindak perusuh demi menjaga stabilitas daerah.
Seruan semacam ini mengingatkan kita pada masa lalu. Kita masih ingat tahun 1998, ketika bangsa berada di ambang krisis yang mengguncang sendi-sendi negara. Kala itu, suara-suara moral hadir sebagai penyejuk. Para tokoh agama dan pimpinan ormas tampil dengan ketulusan. Mereka belum tercemar kepentingan kekuasaan. Suara mereka jernih, seruannya didengar.
Ketika suhu sosial memanas, kehadiran mereka menenangkan. Suara moral saat itu bukan sekadar gema, melainkan cahaya penunjuk arah.

Pada 1998, tokoh-tokoh moral hadir sebagai pelita di tengah gelapnya krisis. Mereka tidak membawa kepentingan selain keberpihakan kepada rakyat. Suara mereka jernih, sederhana, dan menenangkan. Pimpinan ormas agama kala itu berdiri sebagai penuntun moral, bukan penyalur kepentingan politik. Ketika mahasiswa turun ke jalan, tokoh-tokoh moral hadir sebagai penyeimbang: menyalurkan kritik, meredakan emosi, sekaligus mengingatkan penguasa agar tidak buta terhadap suara rakyat.
Kini, peta sudah berubah. Banyak tokoh agama dan pimpinan ormas justru masuk dalam lingkar kekuasaan, atau setidaknya dekat dengan kepentingan politik. Suara yang dulu menyejukkan, kini terdengar formal dan berhitung kepentingan. Alih-alih hadir sebagai suara hati nurani rakyat, mereka sering hanya menjadi penguat legitimasi kebijakan.
Pesan moral kehilangan gaung karena publik menilai: suara itu tak lagi bebas, tak lagi sebening dulu.
Kontras yang Menyakitkan, inilah perbedaan mencoloknya: Dulu, tokoh moral bicara untuk rakyat. Sekarang, banyak tokoh moral bicara di hadapan rakyat, tapi untuk penguasa. Dulu suara mereka mengalir dari nurani, kini kerap tersaring oleh kepentingan.
Pelajaran dari Tragedi Mei 1998
Tragedi kemanusiaan Mei 1998 adalah cermin betapa rapuhnya sebuah bangsa ketika suara moral absen atau dibungkam. Kala itu, meski negara mengerahkan puluhan ribu aparat keamanan, Jakarta justru dibiarkan porak-poranda. Massa yang terorganisir melakukan pembakaran, penyerangan, dan kekerasan brutal, sementara aparat memilih menghilang dari titik-titik krusial.
Yang paling memilukan, etnis Tionghoa menjadi sasaran kebencian. Banyak yang kehilangan harta, martabat, bahkan nyawa. Namun di tengah kegelapan itu, ada cahaya kecil: komunitas-komunitas yang memilih untuk bersatu dan saling melindungi. Di Muara Karang, misalnya, warga yang awalnya tak saling mengenal justru bangkit bersama melawan serangan. Pelajaran yang tak ternilai: tetangga dan komunitas harus menjadi saudara sejati.
Pasca-tragedi, teror dan distorsi informasi ditebarkan. Para sukarelawan, saksi, bahkan korban dibungkam dengan ancaman dan stigma. Namun, suara-suara keberanian tetap hidup. Sukarelawan, guru, pemimpin umat, hingga orang tua sederhana terus menuturkan kisah Mei 1998 sebagai pengingat: bahwa kebenaran dan keadilan tidak boleh mati.
Dari tragedi itu, kita belajar bahwa suara moral bukan sekadar kebutuhan politik, melainkan benteng kemanusiaan. Ketika ia absen, kekerasan dan kebencian mengambil alih. Namun ketika ia hadir, ia mampu menyatukan, menyejukkan, bahkan menyelamatkan.
Janji Manis Peredam Amarah
Gelombang demonstrasi yang meluas pada Agustus hingga September 2025 menjadi bukti bahwa politik tanpa moral hanyalah kerumunan ambisi. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama partai-partai politik, berusaha meredam kemarahan publik lewat berbagai manuver. Ada upaya menonaktifkan kader DPR, seruan menahan diri, hingga pertemuan elite untuk mencari jalan damai. Namun, langkah-langkah itu lebih tampak sebagai janji manis peredam amarah ketimbang solusi substansial.
Kemarahan rakyat tidak lahir dari satu insiden semata, melainkan akumulasi: kenaikan tunjangan DPR yang berlipat, gaya hidup mewah pejabat, utang negara yang membengkak, hingga kebijakan fiskal yang dianggap menekan rakyat kecil. Ledakan itu kian membara setelah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Peristiwa itu menjelma simbol: betapa negara bisa begitu dingin terhadap warganya sendiri.
Pembakaran kantor kepolisian, perusakan gedung DPRD, hingga penyerangan rumah pejabat memperlihatkan bagaimana kemarahan yang kehilangan saluran moral bisa berubah menjadi amuk massa. Di sinilah absennya suara moral terasa nyata. Rakyat tidak lagi percaya pada seruan elite politik yang penuh basa-basi. Mereka merindukan suara yang benar-benar jernih, tulus, dan membela mereka tanpa syarat.
Ketika suara moral kehilangan gaungnya, ruang kosong itu diisi oleh kemarahan tanpa arah. Janji-janji politik hanya mampu menunda, bukan menyembuhkan. Yang dibutuhkan bukan sekadar strategi peredaman, tetapi kehadiran panutan moral yang sanggup mengembalikan kepercayaan.
Dari Panggung Rakyat ke Panggung Kekuasaan
Ada masa ketika suara moral begitu jernih, memantul dari hati nurani rakyat dan menggema di ruang publik. Kita masih ingat tahun 1998, ketika bangsa ini berdiri di tepi jurang krisis. Kala itu, di tengah hiruk-pikuk demonstrasi dan ketegangan politik, suara tokoh-tokoh agama dan moral hadir sebagai penyejuk. Mereka bicara bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kedekatan pada penguasa, melainkan untuk mengingatkan dan menuntun. Suara itu murni, tulus, dan karenanya didengar.
Namun kini, keadaan berbeda. Suara itu tak lagi sebening dulu. Perlahan gaungnya meredup, pesonanya hilang. Banyak tokoh agama dan moral yang dulunya berdiri tegak di tengah rakyat, kini masuk ke pusaran kekuasaan. Mereka duduk di kursi politik, ikut dalam transaksi kepentingan, dan kehilangan jarak kritis. Panggung rakyat yang dulu menjadi rumah mereka, bergeser menjadi panggung elite.
Akibatnya, seruan yang keluar tak lagi meneduhkan. Bukan karena rakyat menutup telinga, melainkan karena suara itu sudah kehilangan ketulusannya. Yang dulu lahir sebagai getar nurani, kini terdengar sebagai siaran resmi: rapi, penuh basa-basi, tapi hampa jiwa.
Melihat fenomena ini, ada dua catatan kritik penting:
Pertama, Dari Moral ke Formalitas. Perubahan ini terasa mencolok. Di masa lalu, suara moral hadir tanpa diminta. Ia muncul sebagai inisiatif murni, hadir untuk merawat keseimbangan di tengah bangsa yang bergejolak. Tokoh-tokoh itu rela menjadi penjaga mata air kebenaran, walau risikonya besar. Kini, banyak suara moral sekadar hadir dalam undangan resmi, dibalut formalitas, terjebak dalam tata krama protokoler. Moral yang dulu membebaskan kini sering terdengar seperti moral yang diborgol.
Kedua, Dari Panutan ke Legitimator. Masyarakat pun merasakan pergeseran ini. Dulu, tokoh moral dipandang sebagai penuntun, panutan yang berdiri di atas segala kepentingan. Kini, sebagian hanya dilihat sebagai legitimator, pelengkap narasi kekuasaan. Tidak lagi menyalakan api keberanian rakyat, melainkan menyalakan lampu sorot di panggung elite.
Mencari Kembali Panutan yang Membumi
Bangsa ini tidak bisa berjalan hanya dengan mesin kekuasaan. Ia butuh suara hati, butuh kompas moral yang menjaga arah. Politik tanpa moral hanyalah kerumunan ambisi; kekuasaan tanpa nurani hanyalah gedung kosong yang bergema oleh kepentingan.
Hari ini, banyak suara moral kehilangan gaungnya. Sebagian larut dalam kenyamanan, sebagian terjebak dalam kedekatan dengan kekuasaan. Namun kehilangan ini bukan akhir, melainkan tanda bahwa kita sedang menunggu kelahiran kembali panutan yang lebih membumi.
Panutan sejati tidak lahir dari sorotan kamera atau panggung istana. Ia lahir dari keberanian menolak fasilitas yang memikat, dari kerendahan hati untuk tetap dekat dengan rakyat, dari konsistensi menyalakan cahaya meski berdiri sendirian dalam gelap. Mereka tidak hanya bicara, tapi juga berani mendengar. Tidak sekadar menenangkan, tapi juga menegakkan kebenaran.
Bangsa ini haus keteladanan. Kita merindukan suara yang mampu menyejukkan di tengah panasnya konflik, menenangkan di tengah gaduhnya perbedaan, dan menghidupkan kembali harapan yang nyaris padam.
Pada akhirnya, suara moral bukan sekadar kata-kata. Ia adalah napas bangsa. Jika ia redup, nurani bangsa pun kehilangan denyutnya. Tetapi bila ia kembali jernih, maka dari panggung rakyat akan lahir kembali energi baru: harapan, keberanian, dan arah yang lebih bermakna bagi masa depan negeri ini.*
Tentang Penulis: Pengurus ICMI Provinsi Banten, Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Mathla'ul Anwar (BRIMA), Dosen di Universitas Mathlaul Anwar Banten.![]()
Dunia 3 hari yang lalu

Opini | 4 hari yang lalu
Olahraga | 5 hari yang lalu
Nasional | 5 hari yang lalu
Nasional | 6 hari yang lalu
Nasional | 4 hari yang lalu
Opini | 3 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Opini | 4 hari yang lalu
Opini | 3 hari yang lalu