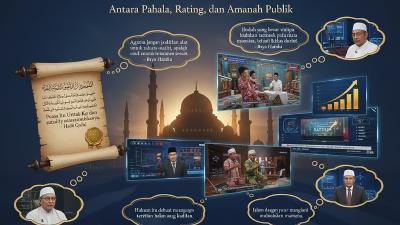Dari Solidaritas Sosial ke Kedaulatan Pangan: MBG dalam Perspektif Sosiologi

RAJAMEDIA.CO - PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Prabowo–Gibran dirancang sebagai upaya strategis untuk menjamin setiap anak-anak sekolah dan ibu hamil memperoleh asupan gizi optimal.
Tak semata merespons krisis stunting, program ini diharapkan menjadi pijakan menuju visi Indonesia Emas 2045 dengan membangun fondasi sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan tangguh. Sasaran MBG mencakup peserta didik dari jenjang SD hingga SMA, santri, anak-anak balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Di tataran global, inisiatif ini berkaitan erat dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin ke-2 (Zero Hunger), ke-3 (Good Health and Well-being), dan ke-4 (Quality Education).
Namun di balik cita-cita mulia itu, program ini juga menuai beragam respons publik; antara harapan dan keraguan. Kasus makanan basi hingga insiden keracunan di sejumlah sekolah menjadi sorotan serius. Di titik inilah, publik mempertanyakan kualitas pelaksanaan serta akuntabilitas dalam rantai produksi dan distribusi pangan MBG.
Meski demikian, tulisan ini tidak hendak mengulas aspek teknokratis atau kebijakan semata. Sebaliknya, tulisan ini membaca MBG dalam perspektif sosiologi. Melalui lensa ini, MBG ini tak hanya menyangkut soal gizi, tetapi juga tentang keadilan dan kohesi sosial, serta arah kedaulatan bangsa.
Pendidikan, dan Ketimpangan
Karl Polanyi pernah mengingatkan bahwa masyarakat modern kerap mencabut pangan dan pendidikan dari akar sosialnya, menjadikannya sekadar komoditas. Dalam sistem seperti ini, makanan bergizi dan pendidikan bermutu menjadi hak istimewa segelintir orang. Orang miskin makan sekadarnya dan sekolah di tempat yang kekurangan fasilitas; sementara kelas atas menikmati gizi berlebih dan sekolah berkualitas tinggi.
Program MBG, dalam konteks ini, bisa dibaca sebagai upaya mengembalikan hak sosial ke dalam bingkai solidaritas. Ketika negara menjamin setiap anak sekolah menerima makanan bergizi, ia bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga meneguhkan kembali prinsip gotong royong dalam wujud yang relevan dengan zaman.
Ini sejalan dengan konsep Emile Durkheim mengenai pentingnya pendidikan sebagai moda integrasi sosial. Dalam semangat itu, aktivitas makan bersama di sekolah dapat menjadi “ritual sosial” yang memperkuat rasa kebersamaan, terutama di tengah keragaman latar belakang ekonomi peserta didik. Sekolah, dengan demikian, tidak hanya menjadi ruang transfer pengetahuan, tetapi juga arena pembentukan nilai empati, kesetaraan, dan kebhinekaan.
Dampak langsung gizi terhadap pendidikan juga tidak bisa diabaikan. Anak dengan asupan nutrisi buruk cenderung kesulitan berkonsentrasi, lebih sering absen, dan tertinggal dalam capaian akademik. Ketimpangan gizi, pada akhirnya, berkontribusi terhadap ketimpangan pendidikan dan memperkuat siklus ketidakadilan sosial.
Pierre Bourdieu menyebut bahwa sistem pendidikan sering kali mereproduksi ketimpangan sosial, karena akses terhadap modal ekonomi, sosial, dan budaya tidak merata. MBG, bila dijalankan dengan sungguh-sungguh, dapat menjadi intervensi struktural yang memutus rantai ketimpangan itu. Dengan memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakangnya, memiliki energi dan gizi yang cukup untuk belajar, negara membuka jalan bagi mobilitas sosial yang lebih adil.
Ini bukan soal logistik semata, tetapi soal siapa yang berhak tumbuh dengan potensi terbaiknya. Namun, potensi itu hanya akan tercapai jika pelaksanaannya melibatkan aktor-aktor lokal. Jika MBG dikuasai segelintir korporasi besar dan dijalankan top-down, ia rentan berubah menjadi proyek bantuan yang bersifat sementara. Sebaliknya, jika dikelola secara partisipatif melibatkan sekolah, masyarakat, dan pedagang dan petani kecil, maka MBG bisa menjadi gerakan solidaritas sosial yang menyatu dengan kehidupan rakyat.
Di sinilah dimensi politik pangan MBG menjadi penting. Apakah bahan pangan bersumber dari petani lokal? Ataukah dari jaringan korporasi besar yang mendominasi rantai pasok? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah MBG mendukung kedaulatan pangan atau justru memperkuat ketergantungan. Bayangkan jika sekolah-sekolah dapat terhubung dengan koperasi, petani lokal, pasar daerah, atau program pertanian berkelanjutan.
Maka, MBG tak hanya memberi makan anak-anak, tapi juga menghidupkan ekonomi akar rumput. Nasi dari petani desa, sayur dari kebun komunitas, dan susu dari peternak lokal. Jika terwujud, ini akan menjadi gerakan solidaritas sosial yang nyata, dari ladang ke ruang kelas. Kedaulatan pangan tidak lahir dari bantuan, tetapi dari partisipasi dan kemandirian.
Agenda Keberlanjutan
Program MBG juga harus dilengkapi dengan pendidikan gizi dan kesadaran lingkungan. Sekolah bisa menjadi ruang belajar kontekstual: tentang asal-usul makanan, proses produksi, hingga dampak ekologis dari pilihan konsumsi. Ini akan sejalan dengan kerangka pemikiran Paulo Freire, bahwa pendidikan bukan sekadar transmisi pengetahuan, melainkan proses pembebasan.
Ketika anak-anak diajak memahami bahwa makan bukan hanya soal kenyang, tetapi juga soal etika dan keberlanjutan, mereka tumbuh sebagai warga yang sadar dan bertanggung jawab secara sosial maupun ekologis. MBG, dalam skenario terbaiknya, bisa menjadi hidden curriculum yang sangat kuat: mengajarkan keadilan, gotong royong, keberlanjutan, dan kepedulian sosial; semua lewat sepiring makanan di ruang makan sekolah.
Jika dijalankan secara konsisten, transparan, dan partisipatif, MBG bukan sekadar kebijakan pangan, melainkan strategi sosial untuk membentuk manusia Indonesia yang berdaya dan berdaulat. Ia bisa menjadi simpul pertemuan antara negara, masyarakat, sekolah, dan petani dalam satu ekosistem solidaritas yang hidup.
Sosiologi mengajarkan bahwa setiap kebijakan publik membentuk struktur sosial baru. MBG bisa memperkuat ketimpangan lama, atau justru membuka jalan emansipasi. Bila dijalankan secara tepat, program ini bisa menjadi tonggak perubahan menuju masa depan bangsa yang lebih adil, sehat, dan berdaulat.
Sebab pada akhirnya, makan bergizi gratis bukan semata soal makanan. Ia adalah cermin dari arah bangsa: apakah kita sedang membangun sistem yang adil dan inklusif, atau sekadar melanggengkan ketimpangan dengan wajah baru.
Penulis: Guru Besar Sosiologi Agama UIN Jakarta*![]()
Daerah 5 hari yang lalu
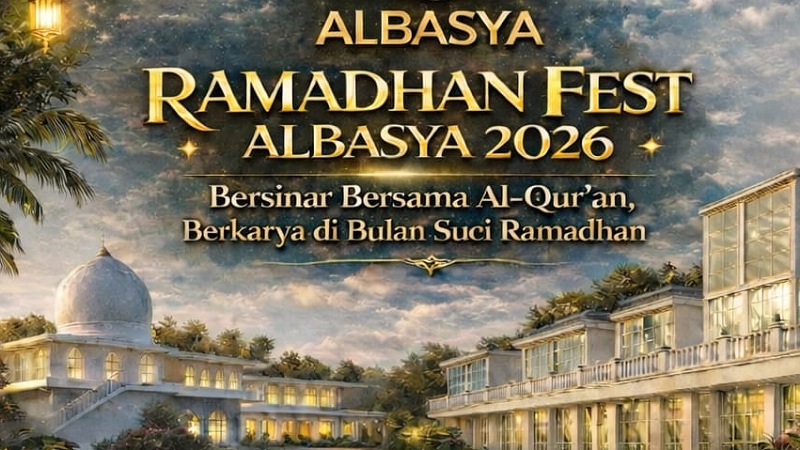
Olahraga | 1 hari yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
Hukum | 4 hari yang lalu
Olahraga | 5 hari yang lalu
Opini | 3 hari yang lalu
Keamanan | 6 hari yang lalu
Olahraga | 5 hari yang lalu
Ekbis | 1 hari yang lalu