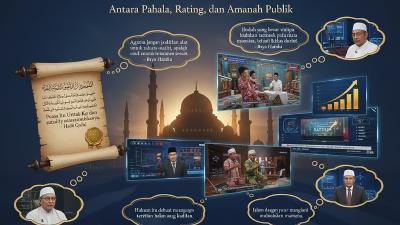Jalan Merunduk atau Berdiri Tegak: Perspektif Lintas Budaya

RAJAMEDIA.CO - BEBERAPA waktu terakhir, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kisruh yang melibatkan salah satu program di Trans7 yang menyinggung relasi kiyai dan santri di pesantren. Tayangan tersebut menimbulkan perdebatan luas: antara yang menilai bahwa sistem pendidikan pesantren terlalu hierarkis dan yang berpendapat bahwa relasi tersebut justru berakar pada tradisi penghormatan dan kedalaman spiritual.
Perdebatan ini sesungguhnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar: bagaimana kebudayaan memahami martabat manusia—apakah dengan jalan merunduk atau dengan berdiri tegak.
Dalam konteks pesantren, relasi kiyai-santri atau guru–murid memang bukan hubungan administratif atau profesional semata, melainkan hubungan batin yang dipenuhi rasa takzim dan kasih. Santri menunduk bukan karena takut, tetapi karena sadar akan keberadaan ilmu dan kehadiran spiritual seorang guru.
Namun dalam dunia modern yang mengutamakan kesetaraan dan kebebasan berpikir, sikap merunduk ini sering disalahpahami sebagai bentuk feodalisme atau kepatuhan buta. Di sinilah kita perlu membaca ulang makna budaya: bahwa menunduk dan berdiri tegak bukan sekadar posisi tubuh, melainkan cermin pandangan hidup manusia.
Di Timur, terutama di Jawa dan Jepang, martabat manusia sering diungkapkan lewat gerak menunduk—simbol kesadaran diri dan rasa hormat. Di Barat, khususnya di Eropa, martabat manusia lebih sering digambarkan dengan berdiri tegak—melambangkan kebebasan berpikir dan keberanian moral.
Dua sikap ini tampak berlawanan, tetapi sesungguhnya keduanya berpangkal pada hal yang sama: penghormatan terhadap kemanusiaan. Perbedaan itu bukan soal tinggi-rendah, melainkan soal cara manusia memaknai hubungan antara diri, sesama, dan semesta.
Jalan Merunduk: Bukan Ekspresi Feodal
Dalam pandangan Jawa, menundukkan kepala bukanlah tanda tunduk kepada kekuasaan, melainkan tanda kesadaran akan keterbatasan diri. Falsafah andhap asor mengajarkan bahwa kemuliaan manusia justru tumbuh dari kerendahan hati.
Orang yang merunduk tidak kehilangan harga diri, melainkan sedang melindunginya. Merunduk menjadi simbol kesediaan untuk mendengarkan, menghormati, dan menyatu dengan alam serta sesama.
Di Jepang, sikap serupa termanifestasi dalam tradisi ojigi—membungkuk sebagai bentuk penghormatan. Tindakan ini bukan hasil tekanan hierarki sosial, tetapi lahir dari nilai-nilai moral yang tertanam dalam kesadaran kolektif.
Dalam budaya Jepang, membungkuk kepada orang lain berarti mengakui keberadaan mereka, menegaskan bahwa kehidupan adalah ruang saling menghormati. Dari sinilah lahir kedisiplinan dan ketertiban sosial yang menjadi ciri khas bangsa Jepang.
Kedua budaya Asia Timur ini menunjukkan bahwa merunduk tidak sama dengan menyerah. Ia justru menjadi bentuk kekuatan batin yang lembut. Dalam keheningan dan kesabaran, terdapat daya yang menaklukkan kesombongan dan ego.
“Jalan merunduk” adalah jalan orang yang matang dalam rasa—mereka yang telah belajar bahwa kekuasaan sejati tidak datang dari posisi tinggi, tetapi dari hati yang jernih dan sadar diri.
Berdiri Tegak: Bukan Keangkuhan
Sementara itu, di Eropa, manusia diajarkan untuk berdiri tegak. Tradisi ini mengakar dalam semangat Renaisans dan Pencerahan, ketika manusia mulai memandang dirinya sebagai makhluk bebas dan rasional. Berdiri tegak berarti berani berpikir sendiri, mempertanyakan dogma, dan menolak penindasan.
Dari sanalah lahir humanisme: pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat moral dan pengetahuan.
Namun, berdiri tegak bukan berarti bersikap sombong. Dalam humanisme Eropa, terutama pada pemikir seperti Erasmus, Kant, dan Montaigne, kebebasan selalu disertai tanggung jawab. Manusia yang berdiri tegak harus menjaga agar kebebasannya tidak melukai orang lain.
Ia berdiri bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk menegakkan keadilan dan martabat manusia. Dalam arti ini, sikap tegak menjadi simbol keberanian moral, bukan kesombongan intelektual.
Dengan demikian, “berdiri tegak” adalah ekspresi kematangan nalar dan hati. Ia melengkapi “jalan merunduk” yang lahir dari kedalaman rasa. Bila merunduk melatih kepekaan dan empati, maka berdiri tegak melatih nalar dan integritas. Keduanya sama-sama membangun manusia yang utuh—manusia yang tahu kapan harus rendah hati dan kapan harus tegas.
Dua Sisi Wajah Peradaban Manusia
Jalan merunduk dan berdiri tegak pada dasarnya bukan dua kutub yang saling bertentangan, tetapi dua sisi wajah peradaban manusia. Dari Timur, kita belajar tentang kehalusan rasa dan kesadaran batin; dari Barat, kita belajar tentang kebebasan berpikir dan tanggung jawab moral. Dunia yang sehat memerlukan keduanya: kepekaan yang lembut dan keberanian yang teguh.
Sayangnya, dunia modern sering kali kehilangan keseimbangan itu. Budaya digital mendorong manusia untuk selalu tampil, bersuara, dan menonjol. Nilai kerendahan hati terpinggirkan oleh logika kompetisi dan pamer.
Di sisi lain, tuntutan “merunduk” kadang disalahartikan menjadi kepatuhan buta terhadap otoritas. Padahal, baik Timur maupun Barat sebenarnya mengajarkan keseimbangan antara hati dan nalar, antara keheningan dan keberanian.
Dalam konteks pendidikan dan kemanusiaan, keseimbangan ini sangat relevan. Guru yang merunduk dengan rendah hati kepada murid, namun berdiri tegak membela nilai kebenaran, adalah cermin ideal dari kebijaksanaan lintas budaya.
Ia tahu bahwa menghormati manusia tidak berarti kehilangan prinsip, dan mempertahankan prinsip tidak berarti kehilangan kesopanan.
Penutup
“Jalan merunduk atau berdiri tegak” pada akhirnya bukan pilihan antara dua jalan, melainkan panggilan untuk menyatukan keduanya dalam kehidupan.
Dari Timur, kita belajar bagaimana hati menjaga harmoni; dari Barat, kita belajar bagaimana pikiran menegakkan keadilan. Dunia membutuhkan manusia yang bisa berjalan di antara keduanya—yang mampu menunduk dengan hormat tanpa kehilangan martabat, dan berdiri tegak tanpa kehilangan kelembutan.
Ketika manusia mampu memadukan keheningan Timur dan keberanian Barat, lahirlah peradaban yang matang: peradaban yang berjiwa lembut, berpikir jernih, dan berperilaku manusiawi.
Maka, di tengah hiruk-pikuk zaman yang sering kehilangan arah, mungkin inilah jalan terbaik: berjalan dengan kepala yang kadang merunduk, dada yang kadang tegak, dan hati yang selalu tunduk kepada kemanusiaan.
Penulis: Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa![]()
Daerah 5 hari yang lalu

Olahraga | 1 hari yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
Hukum | 4 hari yang lalu
Olahraga | 5 hari yang lalu
Opini | 3 hari yang lalu
Keamanan | 6 hari yang lalu
Olahraga | 5 hari yang lalu
Ekbis | 1 hari yang lalu