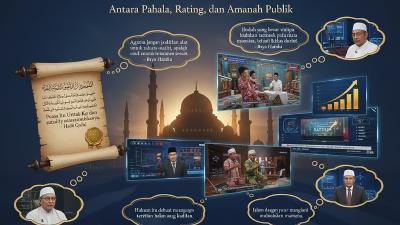Islam Jalan Tengah, Wajah Dua Ulama Banten

RAJAMEDIA.CO - BANTEN, tanah yang sejak lama dikenal sebagai persemaian pejuang dan ulama, kembali menghadirkan dua sosok besar yang menjadi cermin kebesaran Islam Nusantara: Abuya Muhtadi Dimyathi dan KH. Embay Mulya Syarief.
Mereka bukan sekadar ulama, tetapi penjaga nurani bangsa. Abuya Muhtadi, dengan kharisma sufistiknya, mewarisi keteguhan tradisi pesantren dan kearifan lokal yang membumi. Sementara KH. Embay tampil dengan semangat modernitas—tegas, progresif, namun tetap hangat—menjembatani agama dan realitas sosial kontemporer.
Dalam diri keduanya, Islam hadir sebagai jalan tengah: tegas namun penuh welas asih, sufistik sekaligus intelektual, tradisional tetapi visioner. Mereka memperlihatkan bahwa keimanan sejati tidak pernah terjebak dalam ekstremitas, melainkan mampu merangkul zaman tanpa kehilangan akar.
Abuya Muhtadi Dimyathi: Sufi, Santun, dan Panutan Moral
Banten selalu dikenal sebagai tanah ulama, tempat di mana spiritualitas dan perjuangan kebangsaan bertemu dalam satu napas. Dari rahim tanah Pandeglang, lahirlah seorang ulama besar yang menjadi simbol kebijaksanaan sekaligus penjaga tradisi Islam Nusantara: Abuya Muhtadi Dimyathi.
Lahir pada 26 Desember 1953 di Cidahu, Abuya Muhtadi mewarisi garis keilmuan ulama klasik yang kokoh. Sebagai mufti Syafi’iyyah sekaligus mursyid Tarekat Syadziliyah, ia bukan hanya pewaris ilmu, tetapi juga penjaga mata air spiritual yang menghidupi masyarakat Banten hingga hari ini.
Sejak usia muda, Abuya menempuh jalan kesufian dengan kedisiplinan luar biasa. Pada umur 18 tahun, ia menjalani shaumuddahri—puasa setiap hari sepanjang hidupnya. Laku spiritual ini bukan hanya ibadah pribadi, tetapi juga penegasan otoritas moral dan kesungguhan pengabdian kepada Allah. Dari kesungguhan inilah terpancar kewibawaannya sebagai ulama sufi yang disegani, bukan karena gelar, tetapi karena keteladanan hidupnya.
Keilmuannya terasah melalui penguasaan mendalam atas kitab-kitab salaf yang menjadi rujukan utama dalam tradisi pesantren, mulai dari Tafsir Ibnu Katsir, Kutub As-Sittah, hingga Tuhfatul Muhtaj. Abuya tidak sekadar mengajarkan teks, tetapi menghidupkan teks itu dalam keseharian umat. Ia memosisikan diri sebagai penjaga tradisi pesantren yang hidup, bukan sekadar pewaris formal.
Namun, kebesaran Abuya tidak semata terletak pada keluasan ilmu. Yang membuatnya berbeda adalah karakter santun dan rendah hati. Di Pondok Pesantren Roudotul Ulum, ia membuka majelis ta’lim dengan penuh kelembutan, menjadikan setiap pertemuan sebagai ruang penyucian jiwa sekaligus pengayaan intelektual. Setiap Sabtu, Ahad, dan Senin, ia mengajarkan kitab kuning dengan gaya khas yang penuh kedalaman, seakan-akan ia sedang menjahit kearifan lokal dengan benang spiritualitas abadi.
Sikap kebangsaan Abuya semakin meneguhkan posisinya sebagai figur moral bangsa. Dalam fatwanya, ia menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat, dari Sabang sampai Merauke. Bagi Abuya, berpegang pada Pancasila adalah bagian dari menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam yang ia ajarkan bukan hanya spiritual, tetapi juga nasionalis dan berkomitmen pada keutuhan republik.
Dengan tegas, ia menolak organisasi-organisasi transnasional yang mengusung agenda politik radikal, seperti Hizbut Tahrir Indonesia. Bagi Abuya, gerakan semacam itu adalah bentuk pemberontakan terhadap konsensus kebangsaan. Ia meneguhkan bahwa Islam tidak boleh bertentangan dengan Indonesia; sebaliknya, Islam harus menjadi pilar moral yang memperkuat kebangsaan.
Dari titik inilah, Abuya Muhtadi menjelma bukan hanya sebagai ulama Banten, tetapi juga teladan harmoni antara tradisi dan modernitas. Ia menunjukkan bahwa Islam dapat hadir dengan wajah yang teduh, ramah, dan bersahabat dengan kebangsaan. Figur seperti Abuya menjadi bukti bahwa ulama sejati tidak hanya berperan sebagai guru agama, melainkan juga sebagai penjaga akhlak publik, perekat persaudaraan, dan benteng moral bangsa.
Ketika dunia dilanda krisis identitas dan polarisasi, Abuya Muhtadi menghadirkan jawaban sederhana: kembali kepada tradisi yang ikhlas, kembali kepada akhlak, dan kembali kepada kebangsaan. Dari kesufiannya yang dalam, lahir kebijaksanaan yang menenangkan. Dari kesantunannya, lahir keteladanan yang mempersatukan. Dan dari fatwanya, lahir keyakinan bahwa agama dan negara dapat berjalan seiring dalam harmoni, tanpa harus saling menegasikan.
KH. Embay Mulya Syarief: Ulama Progresif dan Jembatan Perubahan
Jika Abuya Muhtadi Dimyathi merepresentasikan akar tradisi sufistik Banten, maka KH. Embay Mulya Syarief tampil sebagai wajah modern yang meneguhkan relevansi Islam di tengah perubahan zaman. Embay adalah ulama progresif yang tidak berhenti pada mimbar dan kitab, melainkan turun langsung ke jantung masyarakat. Ia menghadirkan Islam yang membumi, menyapa petani di sawah, nelayan di pesisir, sekaligus intelektual di ruang-ruang akademik dan forum nasional.
Sebagai tokoh yang menggabungkan intelektualitas muslim dengan semangat aktivis sosial, Embay telah lama dikenal sebagai pelopor gerakan civil society di Banten. Baginya, pesantren bukan hanya ruang pengajaran kitab kuning, tetapi juga laboratorium perubahan sosial. Di sinilah ia meneguhkan gagasan bahwa Islam jalan tengah harus hadir bukan sekadar sebagai wacana, tetapi sebagai energi praksis yang menyelesaikan problem nyata masyarakat.
Islam jalan tengah versi Embay adalah moderasi yang hidup, bukan jargon. Ia memadukan tradisi pesantren dengan kebutuhan zaman: menjaga akar, tetapi sekaligus berani berinovasi. Ia menolak pandangan eksklusif yang membenturkan agama dengan negara, atau tradisi dengan modernitas. Bagi Embay, keduanya justru harus bersinergi demi kesejahteraan umat.
Keberanian Embay dalam menyuarakan perubahan lahir dari pandangan bahwa ulama harus menjadi jembatan antara nilai dan realitas. Ia mengartikulasikan Islam bukan hanya dalam bahasa kitab, tetapi juga dalam bahasa sosial, politik, dan budaya. Dari advokasi masyarakat miskin hingga upaya meredam polarisasi sosial, ia meneguhkan bahwa agama adalah motor transformasi, bukan sekadar simbol identitas.
Kepemimpinan Embay bersifat inklusif dan humanis. Tegas dalam prinsip, namun hangat dalam pendekatan. Inilah yang membuatnya diterima oleh berbagai kalangan, baik di akar rumput maupun di lingkaran elite nasional. Ia adalah sosok yang mampu berdebat tajam dengan intelektual, sekaligus merangkul masyarakat kecil dengan bahasa yang sederhana.
Melalui kiprah panjangnya, Embay menegaskan bahwa Islam dapat menjadi kekuatan emansipatoris, membebaskan masyarakat dari keterbelakangan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Ia bukan sekadar pewaris tradisi ulama klasik, tetapi juga pengolah tradisi itu menjadi solusi nyata bagi tantangan kontemporer.
Di tengah derasnya arus ekstremisme di satu sisi dan sekularisme di sisi lain, Embay menghadirkan jalan ketiga: Islam moderat yang berorientasi pada kemaslahatan. Inilah wajah Islam progresif yang mengakar pada nilai, namun terbuka terhadap dinamika modernitas.
Dengan segala kiprahnya, KH. Embay Mulya Syarief menjelma sebagai figur kunci yang menegaskan bahwa ulama sejati bukan hanya penjaga tradisi, melainkan juga arsitek perubahan. Ia adalah bukti hidup bahwa Islam Nusantara mampu menghadirkan harmoni antara iman, ilmu, dan amal; antara kearifan masa lalu dan tuntutan masa depan.
Harmoni Tradisi dan Modernitas
Dalam lanskap Islam Nusantara, Abuya Muhtadi Dimyathi dan KH. Embay Mulya Syarief adalah dua figur yang seolah mewakili dua kutub: tradisi yang berakar kuat dan modernitas yang bergerak dinamis.
Namun, alih-alih berhadapan, keduanya justru menunjukkan bagaimana tradisi dan modernitas dapat berpadu, saling menopang, dan menghadirkan wajah Islam yang teduh sekaligus progresif.
Abuya Muhtadi hadir sebagai penjaga akar. Dengan sufisme, keteladanan moral, dan kearifan lokal yang ia hidupi, ia memastikan bahwa spiritualitas tetap menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Di tangannya, tradisi pesantren bukan sekadar warisan, melainkan sumber energi moral yang menjaga identitas bangsa. Ia mengingatkan bahwa Islam tidak boleh kehilangan ruhnya: kesantunan, keikhlasan, dan penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan ulama.
Sementara itu, KH. Embay Mulya Syarief membawa Islam ke horizon yang lebih luas. Melalui moderasi, intelektualitas, dan keberanian sosial, ia menegaskan bahwa Islam tidak boleh berhenti pada nostalgia, tetapi harus hadir dalam ruang publik sebagai solusi nyata. Ia menjadikan pesantren bukan hanya tempat pengajaran kitab, tetapi juga pusat transformasi sosial yang menjawab tantangan zaman: ketimpangan ekonomi, polarisasi politik, hingga krisis kebangsaan.
Kedua tokoh ini, dengan pendekatan berbeda, justru bertemu pada satu titik: otoritas moral dan kepedulian sosial. Abuya Muhtadi menjaga akar agar bangsa tidak tercerabut dari identitasnya, sementara Embay membentangkan sayap agar Islam dapat terbang tinggi menjawab tuntutan modernitas. Mereka adalah dua sisi mata uang Islam Nusantara—berbeda rupa, tetapi satu nilai.
Di tengah dunia yang kerap terjebak antara sekularisme kering dan ekstremisme yang keras, keduanya menampilkan jalan ketiga yang indah: Islam jalan tengah. Mereka menunjukkan bahwa Islam tidak hanya soal teks, tetapi juga konteks; tidak hanya warisan, tetapi juga inovasi. Dengan demikian, Islam tetap relevan di setiap zaman, dari pesantren di Cidahu hingga forum-forum global di kota besar.
Banten melalui mereka bukan sekadar tanah sejarah, melainkan laboratorium hidup bagi harmoni iman dan kemajuan. Dari tradisi yang santun hingga modernitas yang progresif, Banten memperlihatkan bahwa Islam Nusantara bukanlah Islam yang stagnan, melainkan Islam yang berdenyut bersama kehidupan.
Kisah Abuya Muhtadi dan KH. Embay adalah pesan kuat bagi dunia: tradisi dan modernitas tidak harus berseberangan. Dalam harmoni keduanya, lahirlah masyarakat yang lebih adil, beradab, dan penuh harapan.
Islam Jalan Tengah
Kisah Abuya Muhtadi Dimyathi dan KH. Embay Mulya Syarief adalah cermin bagaimana Islam Jalan Tengah hadir dengan wajah teduh sekaligus kokoh, berakar dalam tradisi namun tetap menatap masa depan. Mereka bukan sekadar ulama Banten, tetapi simbol kekuatan Islam Nusantara yang inklusif, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Dalam diri Abuya Muhtadi, tampak Islam yang lembut, sufistik, dan sarat keteladanan moral. Ia mengajarkan bahwa kesantunan adalah kekuatan, dan spiritualitas adalah penopang bangsa. Sementara dalam diri KH. Embay, hidup Islam yang progresif, berani, dan kontekstual. Ia menunjukkan bahwa iman sejati harus berjalan beriringan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik.
Keduanya berpadu menjadi pelita—bukan hanya bagi Banten, tetapi juga bagi dunia Islam. Dari pesantren hingga panggung publik, mereka menegaskan bahwa Islam Jalan Tengah bukan sekadar konsep, melainkan jalan hidup yang menghadirkan keseimbangan antara akal dan hati, tradisi dan modernitas, iman dan kemajuan.
Di tengah krisis identitas global, polarisasi, dan radikalisme, kisah mereka menyampaikan pesan universal: agama sejatinya adalah energi pemersatu, bukan pemecah; cahaya pencerah, bukan api yang membakar.
Warisan Abuya Muhtadi dan KH. Embay adalah warisan dunia. Dari tanah Banten, Islam Jalan Tengah bersuara lantang—bahwa keindahan iman terletak pada kemampuannya merangkul perbedaan, menjaga kemanusiaan, dan menuntun peradaban menuju arah yang lebih adil, damai, dan bermartabat.
Penulis: Dosen Universitas Mathla’ul Anwar Banten*![]()
Daerah 2 hari yang lalu

Ekbis | 6 hari yang lalu
Parlemen | 5 hari yang lalu
Dunia | 5 hari yang lalu
Olahraga | 6 hari yang lalu
Keamanan | 4 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Info Haji | 5 hari yang lalu
Nasional | 6 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu