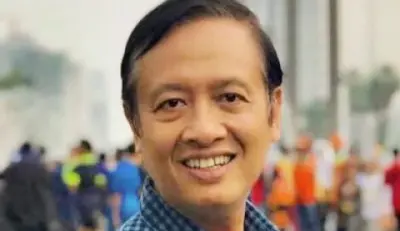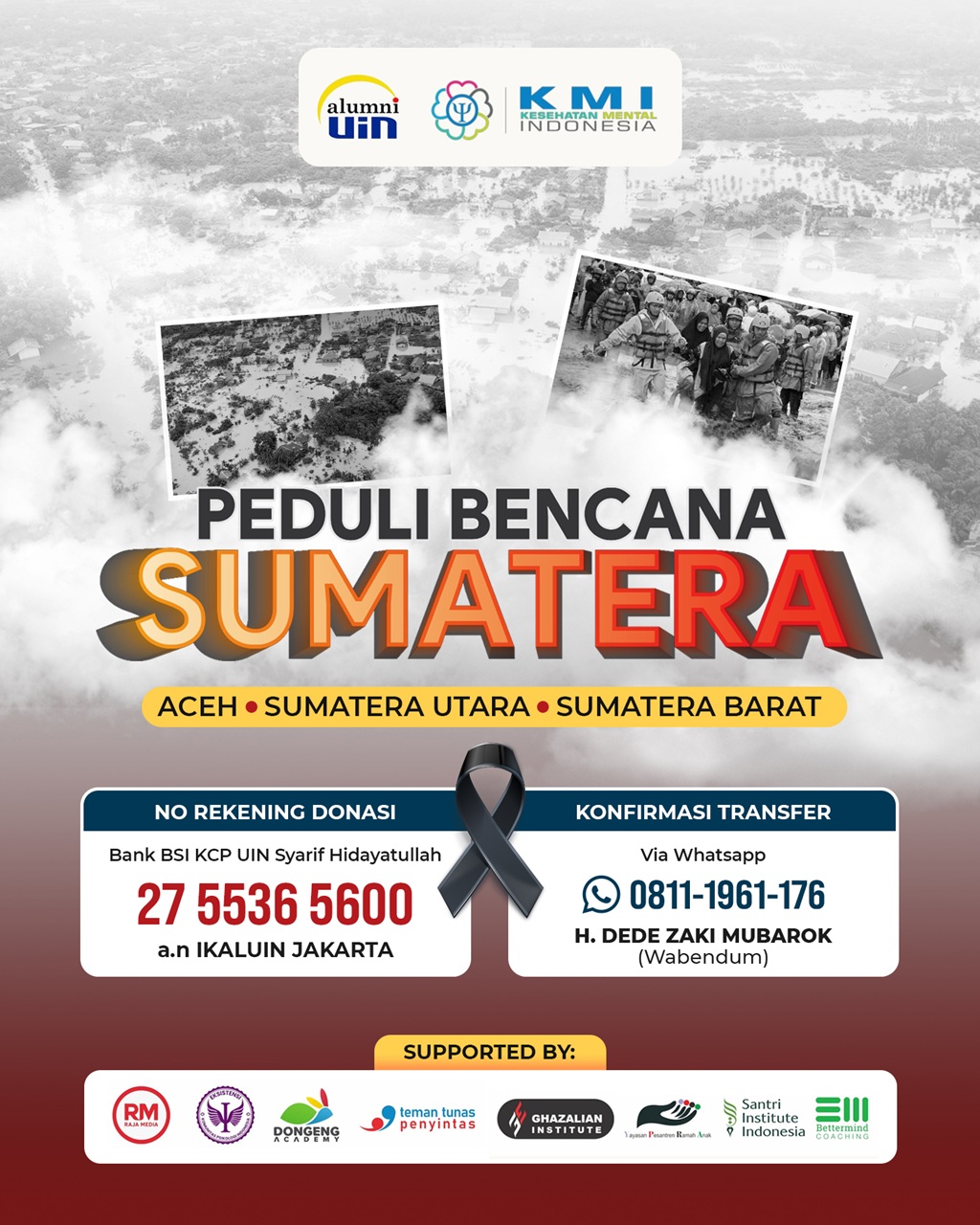Runtuhnya Otoritas Guru Dan Sekolah

RAJAMEDIA.CO - PROFESI guru kembali terguncang. Pristiwa yang menimpa dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Drs. Rasnal dan Drs. Abdul Muis, mengusik dunia pendidikan. Mereka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN setelah Mahkamah Agung memutuskan adanya dugaan pungutan dana komite sekolah.
Aksi damai yang dilakukan rekan-rekan mereka di bawah bendera Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bukan semata solidaritas personal, melainkan ungkapan keresahan kolektif atas hilangnya otoritas moral dan sosial guru di hadapan birokrasi dan publik.
Guru, yang dahulu dihormati sebagai sumber nilai dan penuntun moral, kini terperangkap dalam jebakan regulasi yang kaku. Setiap tindakan kemanusiaan, bahkan yang berangkat dari niat baik seperti mengumpulkan dana untuk kepentingan siswa, dapat berujung pada hukuman administratif. Momen ini menandakan betapa rapuhnya posisi guru dalam sistem pendidikan modern yang lebih menekankan pada kepatuhan prosedural daripada makna pengabdian.
Krisis di Luwu Utara adalah cermin nasional. Ia menunjukkan pergeseran relasi kuasa dalam dunia pendidikan: dari hubungan sosial berbasis kepercayaan menuju hubungan formal berbasis kecurigaan. Sekolah bukan lagi rumah bersama, melainkan institusi birokratik yang tunduk pada administrasi dan hukum positif tanpa mempertimbangkan konteks sosial budaya di balik tindakan guru.
Menyoal Manajemen Berbasis Sekolah
Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada awalnya dimaksudkan untuk mengembalikan kemandirian sekolah dalam mengelola sumber daya, menentukan kebijakan, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Prinsip desentralisasi ini berangkat dari keyakinan bahwa sekolah memahami kebutuhan peserta didik lebih baik daripada birokrat di pusat atau daerah. Namun, setelah dua dekade berjalan, semangat MBS seakan terkubur oleh birokratisasi pendidikan.
Kepala sekolah dan guru kini menjadi perpanjangan tangan sistem, bukan lagi penggerak perubahan. Mereka dituntut inovatif, tetapi setiap inisiatif sering kali terbentur aturan dan ketakutan terhadap audit. Dana komite sekolah yang dulu menjadi simbol partisipasi orang tua kini justru dianggap sebagai potensi pelanggaran. Otonomi sekolah kehilangan maknanya karena regulasi lebih diutamakan daripada kepercayaan.
Akibatnya, guru kehilangan ruang kebebasan pedagogik dan sosial. Setiap keputusan harus menunggu izin berlapis, setiap kegiatan harus sesuai juknis. Sekolah kehilangan daya reflektif dan keberanian untuk berinovasi. Dalam situasi seperti ini, guru tidak lagi menjadi pemimpin moral dan intelektual, tetapi pegawai administrasi yang takut salah langkah.
Kehilangan otonomi ini juga mengikis nilai-nilai gotong royong yang menjadi ciri khas pendidikan Indonesia. Ketika keterlibatan masyarakat dianggap mencurigakan, maka hilanglah semangat kebersamaan yang menjadi fondasi pendidikan lokal. Kasus Luwu Utara hanyalah puncak gunung es dari ketimpangan antara niat desentralisasi dengan praktik sentralistik yang masih kuat dalam sistem pendidikan nasional.
Menata Ulang Tata Kelola Pendidikan Daerah
Pemerintah daerah sebagai penyelenggara satuan pendidikan negeri perlu mengambil langkah berani dan rasional.
Pertama, penerimaan peserta didik baru harus disesuaikan dengan ketersediaan guru ASN dan ruang kelas. Jangan lagi sekolah dipaksa menampung siswa di luar kapasitas karena tekanan politik atau sosial, yang akhirnya membebani guru dan memunculkan praktik informal seperti pungutan.
Kedua, sistem guru honorer perlu diakhiri dengan pengangkatan melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bertahap dan terencana. Kebijakan ini akan memastikan kepastian status, hak, dan perlindungan hukum bagi para pendidik yang selama ini bekerja dalam kondisi tidak menentu. Dengan demikian, kualitas pendidikan menjadi lebih stabil dan profesional.
Ketiga, masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi aktif melalui penguatan dan perluasan peran sekolah swasta. Negara tidak harus menjadi satu-satunya penyedia pendidikan; peran swasta dan komunitas lokal bisa menjadi mitra strategis. Dengan demikian, tekanan terhadap sekolah negeri dapat berkurang, dan guru dapat bekerja dalam lingkungan yang lebih sehat, kreatif, dan otonom.
Keempat, perlu kebijakan nasional dan daerah yang memperkuat kembali Manajemen Berbasis Sekolah dan otonomi sekolah secara substantif. MBS tidak boleh dimaknai sebagai pelimpahan tanggung jawab administratif, tetapi sebagai pemberdayaan komunitas pendidikan untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan lokal. Pemerintah pusat cukup menetapkan standar, sementara pelaksanaan diserahkan pada sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan terdekat dengan masyarakat.
Kelima, Mahkamah Agung dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus lebih jeli, teliti, dan proporsional dalam menafsirkan hukum yang menyangkut profesi guru dan tata kelola pendidikan. Tidak semua tindakan administratif dapat disamakan dengan tindak pidana. Hukum harus dibaca dengan memahami konteks sosial pendidikan, agar keadilan tidak justru melukai nurani pendidik yang bekerja dengan niat baik. Pengadilan hendaknya menjadi tempat keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum.
Keenam, sudah saatnya mengakhiri paradigma negatif sebagian LSM dan pengamat pendidikan yang cenderung memandang sekolah dan guru dengan kacamata kecurigaan. Kritik sosial memang penting, tetapi seharusnya konstruktif dan kontekstual. Pendidikan adalah ekosistem sosial yang kompleks, bukan ruang transaksional yang bisa dihakimi sepihak. Bila semua upaya gotong royong dianggap salah, maka nilai-nilai sosial khas Indonesia akan sirna di tangan generasi kita sendiri.
Akhirnya, mengembalikan otoritas guru berarti mengembalikan ruh pendidikan itu sendiri. Guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, tetapi penjaga nurani bangsa. Bila kepercayaan pada guru runtuh, maka pendidikan kehilangan makna kemanusiaannya. Kasus Luwu Utara harus menjadi pelajaran bahwa sistem pendidikan yang sehat bukan yang paling patuh pada aturan, melainkan yang paling berpihak pada nilai, martabat, dan kemandirian manusia.
Penulis: Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA)![]()
Daerah 5 hari yang lalu

Daerah | 6 hari yang lalu
Kesehatan | 4 hari yang lalu
Nasional | 5 hari yang lalu
Olahraga | 6 hari yang lalu
Parlemen | 6 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Daerah | 5 hari yang lalu
Keamanan | 6 hari yang lalu
Nasional | 4 hari yang lalu