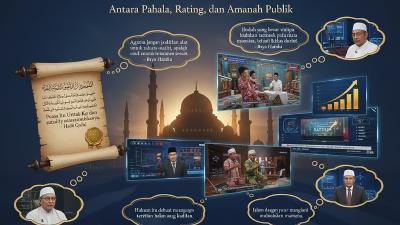Kecerdasan Buatan (AI) dan Agama

RAJAMEDIA.CO - SEORANG Gen Z bertanya pada chatbot : “Apa hukumnya meninggalkan shalat karena Lelah bekerja ?” Dalam hitungan detik, ia menerima jawaban lengkap dengan dalil al Qur’an, hadits dan fikih dalam berbagai mazhab. Tak ada guru, tak ada ustadz hanya layer ponsel dan kecerdasan buatan.
Di tengah gelombang digitalisasi, agama dan kecerdasan buatan kini tidak lagi berjarak. Teknologi yang dulu dianggap dingin dan tidak bernyawa, perlahan memasuki ruang ruang batin manusia yang selama ini hanya diisi oleh doa, keyakinan dan pencaharian makna hidup.
Agama dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berasal dari dua dunia yang berbeda Agama berasal dari wahyu dan tradisi spiritual, berakar pada nilai-nilai transcendental yang diwariskan secara turun temurun dan sacral. Sementara AI adalah buah dari rasional manusia modern yang mengandalkan logika, data dan algoritma. Kecerdasan buatan adalah profane. Saat ini keduanya saling terkait, bahkan dalam beberapa hal saling mempengaruhi.
Beth Singler, dala penelitiannya membagi relasi agama dan AI kedalam tiga fase. Fase pertama, fase penolakan (rejection), kedua fase penerimaan (adoption) dan fase ketiga,penyesuaian (adaptation). Pada fase pertama, komunitas keagamaan merespons AI dengan rasa takut bahwa peran manusia dalam kehidupan spiritual akan tergeser. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pertimbangan rasional mulai mengemuka. Banyak komunitas agama akhirnya mengadopsi AI karena manfaatnya yang besar dan efisiensinya yang tinggi.
Kini kita memasuki fase adaptasi, AI bukan hanya digunakan untuk aktivitas administrative dan promosi dakwah, tapi juga untuk membuat bahan ceramah, menelusuri dalil hokum, bahkan menjawab pertanyaan keagamaan secara langsung.
Dalam konteks ini AI perlahan menjadi bagian dari kebiasaan sosial baru dalam kehidupan beragama. Ia hadir sebagai “dewa penolong” yang mudah diakses, murah,dan responsive. AI kini telah menjadi bagian dari habitus baru, meminjam istilah Bordieu, dalam kehidupan spiritual masyarakat modern.
Namun, kehadiran AI yang begitu luas ini menimbulkan pertanyaan filosofis dan teologis. Dalam Islam manusia dimuliakan karena kemampuannya berfikir. Akal adalah anugerah Ilahi yang menjadikan manusia lebih tinggi derajatnya dari makhluk yang lain. Akal menjadi landasan utama bagi tanggungjawab manusia sebagai khalifah di bumi.
Jika AI kini melampaui manusia dalam beberapa aspek berfikir dan mengambil keputusan, maka umat Islam perlu menakar ulang peran dan keunggulan spiritalnya. Jika AI kini mampu berfikir, menganalisis, bahkan memberi nasehat spiritual, maka peran unik manusia mulai dipertanyakan. Apakah umta Islam bisa tetap relevan dan unggul ditengah lonjakan kecerdasan buatan ?
Di Indonesia penggunaan AI semakin mmeluas dalam berbagai bidang seperti Pendidikan dan pekerjaan manusia, namun masih banyak dimanfaatkan untuk hiburan intelektual dan spiritual. AI justru memperkuat budaya konsumtif pasif. Jika tidak diimbangi dengan literasi digital dan kesadaran kritis, umat Islam bisa semakin tertinggal dalam persaingan global.
Lebih dari sekadar persoalan akses, tantangan utama terletak pada cara berfikir umat terhadap teknologi ini. Banyak diantara kita yang belum memandang AI sebagai alat strategis untuk membangun masa depan umat, melainkan sekadar sebagai pelengkap gaya hidup. Padahal di negara negara lain, AI telah digunakan untuk mengembangkan aplikasi tafsir digital, platform belajar daring berbasis kitab kuning hingga system prediktif untuk penentuan awal Ramadhan dan waktu shalat berbasisastronomi mutakhir. Jika potensi ini tidak segera digarap secara serius kita berisiko kembali menjadi konsumen pasif dalam lanskap peradaban digital global.
Pertemuan AI dan agama juga memunculkan dinamika baru dalam hal otoritas keagamaan. Dahulu jawaban keagamaan hanya bisa diberikan oleh mereka yang mendalami ilmu fikih dan usul. Kini cukup dengan membuka aplikasi, siapa pun bisa mendapat jawaban dari AI dalam waktu singkat. Walaupunsecara keilmua belum tentu dapat menggantikan ijtihad ulama, tren ini terus menguat, terutama dikalangan generasi muda.
Dalam bukunya Religion and Artificial intelligence (Routledge, 2025), Singler mengungkap bahwa agama dan AI kini berada dijalur yang sama, persimpangan yang akan menentukan wajah keagamaan dunia ke depan. Dengan 84% penduduk bumi masih memeluk agama agama besar, potensi perubahan sosial dan spiritual akibat AI bukan sekadar spekulasi. Dalam konteks sosiologi agama, AI berpotensi menggugat posisi agama sebagai otoritas tertinggi dalam hal moral dan tindakan.
AI juga membawa penguatan rasionalitas, bahkan narasi baru yang lebih logis dan sistimatis. Bila tidak dikelola, kekuatan naratif ini dapat menyaingi bahkan menggantikan, otoritas agama tradisional. Dalam jangka Panjang ini bisa, melahirkan gelombang ateisme digital yang tumbuh bukan dari penolakan terhadap Tuhan, melainkan karena ketergantungan pada mesin yang dianggap lebih netral dan factual.
Namun tantangan ini tidak harus dihadapi dengan ketakutan dan penolakan. Sebaliknya, komunitas agama perlu membangun sikap yang cerdas, kritis, dan proaktif. AI bisa menjadi alat bantu dalam dakwah, Pendidikan, dan distribusi ilmu keagamaan. Dengan pendekatan yang tepat, AI justru bisa membantu memperluas jangkauan nilai-nilai spiritual kepada generasi yang makin digital.
Yang perlu dijaga adalah keadaran bahwa AI secerdas apa pun, tetaplah buatan manusia. Ia tidak memiliki kesadaran, nurani, niat dan tanggungjawab moral. Keputusan etis dan spiritual tetap menjadi ranah manusia. Maka tugas umat beragama bukan hanya memahami teknologi, tetapi juga menanamkan nilai untuk membimbing penggunaannya.
Ditengah riuhnya inovasi digital, iman tetaplah ruang sunyi yang tak tergantikan. AI bisa membantu kita menjawab pertanyaan pertanyaan agama, tetapi hati manusia yang bisa memahami dan mangalami makna makna agama.
AI mungkin bisa menjelaskan peroslan persoalan teologis keagamaan dengan narasi yang meyakinkan, tetapi hanya manusia yang dapat merasakan kedekatan dengan sang pencipta. JUatru karena itu masa depan spiritualitas tidak akan ditentukan oleh algoritma, melainkan oleh manusia yang mampu menjadikan teknologi sebagai jalan menuju pencerahan, bukan keterasingan.
Penulis: Guru Besar Sosiologi Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*![]()
Daerah 6 hari yang lalu

Nasional | 5 hari yang lalu
Keamanan | 6 hari yang lalu
Opini | 6 hari yang lalu
Nasional | 5 hari yang lalu
Daerah | 5 hari yang lalu
Ekbis | 4 hari yang lalu
Peristiwa | 5 hari yang lalu
Daerah | 6 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu