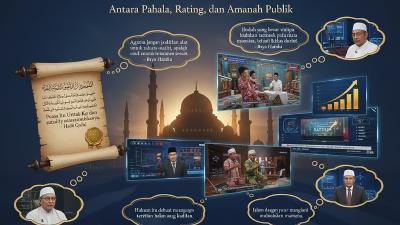Demokrasi Kita Membutuhkan Agama

RAJAMEDIA.CO - SEPERTI pungguk merindukan rembulan. Peribahasa itu tampaknya cukup mewakili kegelisahan kolektif kita menjelang tiga dekade era reformasi. Harapan akan penguatan demokrasi dan meningkatnya kesejahteraan rakyat semakin terasa bertepuk sebelah tangan.
Deretan peristiwa yang mengejutkan publik—mulai dari polemik permintaan kenaikan gaji anggota DPR, arogansi Bupati Pati, hingga kasus korupsi yang menyeruak di berbagai level pemerintahan, kementerian, dan BUMN—semuanya menjadi bukti bahwa sistem demokrasi kita tengah berjalan ke arah yang disfungsional, bahkan merosot.
Kekuasaan yang idealnya dijalankan dengan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel demi kemajuan bersama, kini malah dibelokkan demi melanggengkan kepentingan sempit para elit. Demokrasi yang semestinya menjadi jalan menuju keadilan sosial justru menjelma menjadi arena penguatan oligarki. Demokrasi prosedural terus berlangsung, tetapi esensinya luntur.
Banyak yang merasa pesimis dan tidak aman melihat perkembangan demokrasi Indonesia saat ini. Kasus terbaru Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan menambah deretan bukti bahwa demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional, telah berubah menjadi alat untuk memperkaya segelintir penguasa. Demokrasi yang seharusnya menjadi laboratorium partisipasi rakyat, kini sering kali dikendalikan oleh oligarki kecil yang menutup telinga terhadap kritik publik.
Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia menghadapi problem serius, yakni maraknya politik transaksional, tumbuh suburnya dinasti politik, dan lemahnya kontrol sosial masyarakat. Demokrasi kian kehilangan daya hidup. Ia berjalan sebagai rutinitas lima tahunan, namun miskin makna dan arah dalam upaya menyejahterakan rakyat.
Krisis Resonansi
Kini, kita seolah hidup dalam ruang publik demokasi yang kehilangan visi, ide, dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Krisis demokrasi yang kita alami sebenarnya tidak perlu terjadi, andai para elit memiliki kemauan untuk mendengar dan merasakan denyut nadi rakyat. Jika saja para pemegang kekuasaan menunjukkan empati, perhatian, dan kepedulian yang tulus terhadap realitas kemiskinan serta aspirasi rakyat kecil, mungkin kita sudah lebih dekat dengan hakikat sejati 80 tahun usia kemerdekaan saat ini.
Sosiolog Jerman, Hartmut Rosa, mengingatkan bahwa demokrasi sejati hanya tumbuh di atas dasar proyek bersama dan kesediaan untuk menumbuhkan hati yang saling mendengarkan (listening heart). Setiap warga negara, siapa pun dia, harus dilibatkan dalam membangun masa depan bersama untuk menciptakan “rumah bersama” yang inklusif.
Sayangnya, saat ini demokrasi tengah dirongrong dari dalam oleh mereka yang lebih menginginkan status quo dan pelanggengan kekuasaan. Hubungan antara rakyat dan penguasa menjadi semakin agresif. Kritik dibalas dengan kepongahan, arogansi, dan represi. Diskusi publik kehilangan kualitas karena hanya melahirkan kegaduhan, bukan solusi. Ruang publik pun menjadi bising dan tidak lagi konstruktif.
Dalam atmosfer seperti ini, demokrasi tak akan mampu tumbuh sehat. Demokrasi memerlukan resonansi, yakni kemampuan para elit penguasa untuk mendengar secara sungguh-sungguh, membuka ruang bagi keberagaman suara, dan membangun sikap hati yang terbuka. Tanpa resonansi, demokrasi hanya tinggal prosedur formal, kehilangan ruh, dan mudah dipermainkan oleh elit.
Butuh Agama
Di sinilah letak urgensi agama dalam demokrasi Indonesia. Demokrasi kita membutuhkan agama sebagai sumber nilai-nilai etika dan spiritualitas. Agama yang menanamkan kesadaran akan kerendahan hati, kesabaran, penghormatan, dan cinta kasih terhadap martabat manusia dapat menjadi penyeimbang yang penting dalam era pragmatisme politik yang kian membuncah.
Pertama, agama mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah untuk mengalirkan dan mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian bagi masyarakat. Kekuasaan bukanlah alat pemuas kepentingan pribadi, keluarga, atau lingkaran kelompoknya sendiri.
Kedua, agama mengajarkan resonansi: bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang mau mendengar dan membuka hatinya terhadap suara rakyat kecil. Elit yang tidak punya hati dan telinga untuk mendengarkan berarti tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan.
Ketiga, agama mengajarkan sikap asketis (zuhud), yakni kemampuan menahan diri dari kerakusan dan kecenderungan menumpuk kekayaan pribadi tanpa arah yang jelas. Asketisme memiliki akar dalam semua agama, dan itu sangat dibutuhkan dalam konteks demokrasi di Indonesia saat ini untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Weber dalam “Protestant Ethics and Spirit Capitalism” berargumen bahwa pada kelompok Calvinis Protestan, misalnya, mengajarkan pemeluknya untuk berperilaku hemat dan sederhana.
Sejak awal berdirinya, Indonesia telah menempatkan agama sebagai pilar penting kehidupan berbangsa. Pancasila secara eksplisit menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, menegaskan bahwa nilai moral dan spiritual seharusnya menjadi fondasi demokrasi kita. Jika kemerdekaan adalah berkah dari Tuhan, maka semestinya ada internalisasi nilai-nilai etika agama dalam politik dan demokrasi kita. Dengan kembali pada tradisi dan etika luhur agama, para pemimpin kita diharapkan dapat meneladani para nabi dan rasul: menjadi pemimpin profetik yang mencintai rakyatnya.
Karenanya, demokrasi Indonesia perlu mengalami reorientasi mendalam. Demokrasi tidak boleh dipahami semata sebagai mekanisme elektoral lima tahunan, tetapi sebagai ruang hidup bersama yang etis, bermakna, dan resonan. Nilai-nilai agama dapat memberi arah agar demokrasi tidak terjebak dalam formalitas yang hampa. Kasus-kasus korupsi yang terus bermunculan adalah refleksi bahwa tanpa fondasi moral yang kuat, demokrasi mudah tergelincir menjadi permainan kekuasaan dan kepentingan. Jika kita benar-benar ingin demokrasi tetap hidup dan berfungsi, maka ia harus dipelihara dengan etika, resonansi, dan spiritualitas.
Demokrasi Indonesia membutuhkan agama. Bukan agar menjadi teokrasi, melainkan agar para elit politik kita mau bekerja secara sungguh-sungguh memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat tidak lagi menjadi impian dan harapan semu.
Penulis: Prof. Dr. Yusron Razak, M.A, Guru Besar Sosiologi Agama UIN Jakarta.![]()
Daerah 3 hari yang lalu

Parlemen | 5 hari yang lalu
Dunia | 5 hari yang lalu
Keamanan | 4 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
Hukum | 2 hari yang lalu
Info Haji | 6 hari yang lalu
Parlemen | 4 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu